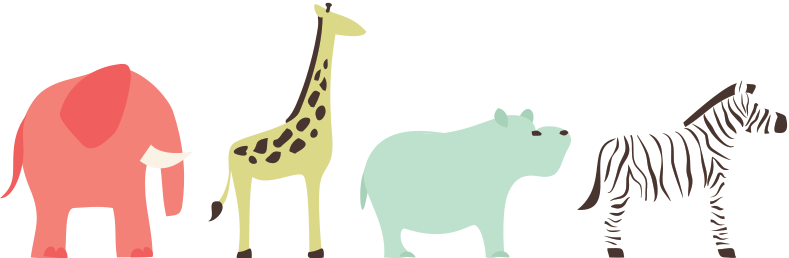Ramadhan semakin dekat. Gampang sekali melihat tandanya, harga-harga pangan mulai melambung. Sudah biasa. Bulan puasa akan datang, tiket-tiket dengan harga murah sudah tak lagi ada. Sudah biasa juga. Sirup-sirup juga acara-acara yang konon religi sudah sliweran di televisi. Sudah rutinitas.
Tidak mau ngomel, itu juga sudah biasa. Tiba-tiba saja sore ini teringat pada yang telah tiada. Aku mau cerita tentang mukena pertama. Aku masih menyimpan sarung pertama, warisan bapak ke emak yang kemudian kubawa ke mana-mana, tapi tidak mukena pertamaku. Mukenaku sudah berganti beberapa kali.
Di sekolah, dasar, setiap pelajaran agama, kami diajari sholat. Kelas tiga waktu itu. Semua murid perempuan diminta membawa mukena. Zaman dulu beli mukena tidak seperti sekarang, anak bayi pun sekarang gampang saja punya mukena. Waktu itu aku hanya pinjam, punya emak, punya kami sekeluarga perempuan. Mukena tak banyak, tidak satu-satu untuk masing-masing anggota keluarga, kami pakai bergantian.
Maka saat pelajaran agama, mukena yang ukuran dewasa itulah mukenaku. Tentu saja kedodoran, badanku tak seperti sekarang yang besar dan berisi, halah. Muka tenggelam, tangan tak tampak, bawah menjuntai seperti kuntilanak. Biasa saja sebenarnya, tak ada teman yang mengolok, karena tidak semua lebih bagus dari punyaku. Lagipula mengolok artinya mencari masalah, denganku.
Namanya anak kecil, merengek adalah senjata. Pingin rasanya punya mukena sendiri, dengan ukuran yang sesuai badanku. Maka glendotan di tangan emak adalah sebuah usaha. Bukan tidak mau tentunya, semua emak waras pasti sama, ingin menyenangkan anaknya. Pun emakku. Maka kami pun ke pasar, membeli kain untuk dijadikan mukena. Kain pun dapat, langsung diberikan ke tukang jahit tetangga. Tak lama mukenaku pun baru.
Saat pelajaran agama berikutnya, belajar sholat sudah pakai mukena sendiri. Sudah bagus, putih dan baru, meskipun gerah. Iya, mukena baruku gerahnya minta ampun. Apalagi sholat bersama yang kami lakukan empat rakaat ditambah bacaan-bacaan, rasanya ingin lari saja. Tapi mukenaku baru, maka aku harusnya bersuka. Gerah hanya kurasakan sendiri, temanku cukup melihat mukenaku baru. Titik.
Tapi bila selalu begitu, tentu tidak nyaman. Apalagi ketika kemudian aku tahu, mukenaku dibuat dari kain kafan yang biasa dipakai untuk orang yang meninggal. Tidak banyak rasanya saat itu, hanya satu rasa saja, takut. Maka ketika teman yang lain sholat buru-buru karena lapar, aku buru-buru karena lapar dan takut. Aku membayangkan aku adalah mayat, orang mati dan untuk anak kelas tiga SD hal itu cukup menakutkan.
Selembar kain kafan dari jenis yang sama yang membungkus seorang kawan, sepuluh ribu hari yang lalu. Selembar kain kafan membalut tubuh emak. Bukan kain katun, bukan pula sutera. Kain kafan, kain yang akan kita pakai kapan saja, pada waktunya. Kain yang gerah dipakai saat ini, tapi kain satu-satunya yang akan menemani kita semua nanti. Al fatihah, untuk mereka-mereka yang saat ini bermukena kafan. Tidak ada lagi gerah, hanya cerah, bersama-Nya.