Surabaya, 14 maret 2011
05.17 WIB
Alarm dari handphone berbunyi, bukan, meraung, entah untuk yang keberapa kali. Tangan mungil meraba, mencoba meraih tombol sekenanya. Kembali hening. Sesosok tubuh di atas ranjang menggeliat. Ditarik selimut yang melorot ke kakinya, dipelukkan ke tubuhnya yang terasa dingin. Kedua matanya masih lekat, seolah tak ingin melepaskan mimpi yang baru mencandai.
Tarikan nafas terdengar halus bergantian dengan hembusan, mengiringi ruh yang kembali melayang. Seorang gadis, ya dia seorang gadis, merajut kembali mimpi yang terpenggal. Tubuh yang masih lelah, masih rindu dipeluk malam itu pasrah, membiarkan ruhnya bermain di alam mimpi, dipermainkan mimpi. Wajahnya yang tenggelam di antara tumpukan bantal terlihat tenang.
Kamar yang tak terlalu luas itu masih gelap. Pintu dan jendela tertutup rapat. Tak terlihat setitik cahaya pun meski di atas pintu dan jendela ada lubang angin. Yang seperti ini mana bisa membedakan pagi dan malam, sama-sama gelap. Gadis masih lelap. Dengkur halusnya adalah irama, mengikuti rintik hujan yang turun sedari malam di luar kamarnya.
Handphone yang tergeletak di samping kepalanya bersuara, menyala, tak lama. Gadis menggeliat. Kembali memperoleh ruhnya, dibuka matanya perlahan. Dikejap-kejapkan untuk beberapa saat, mencoba mengembalikan kendali atas jiwa dan tubuhnya. Sebuah desahan panjang, disusul dengan rentangan kedua tangannya. Buru-buru ditutup mulutnya yang menguap kuat dengan sebelah tangan.
Gadis bangkit, membiarkan selimut yang tadi membalutnya terjatuh, menjuntai sebagian ke lantai kamar. Perlahan dia mulai berjalan menuju ke jendela. Tak sulit meski gelap karena dia hapal betul letaknya. Disibakkan tirai kemudian didorongnya daun jendela keluar. Hembusan angin, basah, langsung menyambutnya, menyentuh wajahnya.
“Hujan,” bisiknya.
Diulurkan tangan kanannya keluar. Dibiarkan rintik hujan membasahi jemari juga telapak tangannya. Bibirnya mulai menyungingkan senyum. Kali ini mulai dipejamkan matanya. Tangan kirinya ikut dijulurkan keluar. Kedua tangannya bergerak, menggeliat, menikmati guyuran dari langit itu. Sebuah teriakan kecil mengagetkannya. Dibuka kedua matanya. Seorang perempuan muda terlihat menggerutu karena bajunya basah. Payung yang digunakannya terbang terseret angin dan jatuh ke atas jalanan yang becek. Gadis tersenyum.
“Hati-hati Mbak,” teriaknya.
Perempuan di jalan itu mendongak, melihat ke arahnya kemudian tersenyum.
“Baru bangun?” tanyanya setengah berteriak.
Gadis mengangguk. Dilambaikan tangannya pada perempuan yang ternyata tetangganya itu. Tak lama, matanya kemudian memandang lurus. Tak jelas apa yang sedang dipandangnya. Puncak-puncak gedung bertingkat, antena di atas genting rumah tetangganya, juluran kabel listrik yang melintang dari satu rumah ke rumah lainnya adalah yang terlihat dari lantai dua rumahnya, dari jendela kamarnya, selain langit yang masih hitam meski jam hampir menunjukkan pukul enam pagi.
Langit masih menumpahkan airnya, tak kuat, hanya rintik-rintik saja. Gerimis. Jalanan di bawah di beberapa sisi tampak becek oleh air yang menggenang. Gadis meletakkan pantatnya di bibir jendela. Sebelah tangannya masih dijulurkan keluar. Matanya masih lurus ke depan, menembus ruang entah berapa kilometer jauhnya. Lagi-lagi bibirnya tersenyum. Di atas langit yang sepertinya sedang berduka itu, seraut wajah tiba-tiba muncul.
“Kamu lihat, seperti bumi yang selalu menanti siraman hujan, seperti itu aku merindukanmu,” bisiknya lirih.
Jogjakarta, 14 Maret 2011
04.25 WIB
Sesosok tubuh tampak terkantuk-kantuk di atas kursinya. Punggungnya terlihat tak lurus, seolah capek menyangga tubuhnya. Di hadapannya sebuah laptop menyala. Barisan kata, dalam kalimat, rangkaian paragraf, tersusun entah sudah berapa lembar. Barisan ide yang diobrak-obriknya. Tak tepat, tak benar, kurang enak, macam-macam pikirannya, membuatnya harus berkali-kali menghapus untuk kemudian menyusunnya kembali kata per kata.
Dia laki-laki. Sebuah cangkir kopi di atas meja, kosong. Isinya telah ludes diteguknya beberapa jam lalu. Asbak penuh dengan puntung-puntung rokok disisi kiri mejanya menandakan pergulatan batin yang keras semalam, masih belum berakhir. Sebatang rokok masih menyala, tergeletak di atas asbak. Laki-laki itu mulai menggaruk kepalanya, entah gatal tapi yang terlihat dia sedikit menarik-narik rambutnya.
“Akh!” pekiknya.
Sayup terdengar suara adzan dari masjid yang tak jauh dari rumahnya. Sayup yang kemudian mengeras dan saling bersahutan dari satu masjid ke masjid lainnya juga mushola. Suara adzan yang menimpali, membuat suara Iwan Fals yang mengalun lirih dari laptopnya tenggelam, tak terdengar.
Laki-laki tertunduk. Kepalanya semakin berat. Puluhan mililiter kafein yang diteguknya sejak semalam tak lagi kuasa membendung kantuknya. Tubuhnya lunglai, lemas. Sampai kapan seperti ini, tanyanya dalam hati. Rokok di atas asbak menyisakan asap yang menari lemah, seolah berjuang antara hidup dan mati. Tak sampai separuh, mungkin seperempat saja, seperti barisan kalimat di hadapannya yang sudah lebih dari separuh untuk diselesaikannya.
Tak ingin berlama-lama dengan pikiran yang tak juga menemukan jalan terang menuju ujung, laki-laki berdiri. Diraih rokoknya untuk kemudian dihisapnya dalam, panjang. Pelan kakinya mulai melangkah mendekati jendela yang dibiarkannya terbuka. Hembusan angin pagi terasa dingin menyentuh ketika didekatkannya wajahnya ke jendela. Kepalanya mulai menjulur keluar, mendongak ke langit yang terlihat hitam.
“Hujan,” bisiknya pelan.
Buru-buru dihisap kembali rokoknya, memaksakan untuk segera habis. Seolah teringat sesuatu, dengan tergesa dia menjauh dari jendela. Dijepit batang rokoknya di antara kedua bibir. Matanya mulai beredar ke seluruh kamar. Kedua tangannya sibuk menggeledah, membongkar-bongkar tumpukan buku juga kertas yang berserakan.
Ah, ketemu juga yang dicarinya. Di atas ranjang benda itu tergeletak. Sebuah handphone, handphone yang entah sudah berapa umurnya. Seingatnya itu adalah handphone kedua setelah handphone pertamanya jatuh dan terlindas mobil ketika dia berangkat ke kampus. Diraihnya benda mungil itu dan kemudian mulai mengetikkan sesuatu.
Tiba-tiba laki-laki tersenyum. Seolah teringat sesuatu yang manis di sebuah masa yang lalu, bibirnya makin mengembang. Dipukul-pukulkan handphone itu ke kepalanya ketika dia tersadar pikirannya telah terlalu jauh melayang. Lagi-lagi dia tersenyum, seperti menertawai dirinya sendiri.
“Aku sudah menghapus nomermu tapi otak bodohku ini ternyata terlalu kuat menyimpan semua hal tentangmu,” katanya dalam hati.
Laki-laki lagi-lagi tersenyum meski sedikit pahit kali ini. Suara adzan sudah berhenti. Suara Iwan Fals kembali terdengar lirih. Suara hujan, meski gerimis mulai memonopoli. Laki-laki meletakkan handphonenya, ah terlalu dilembut-lembutkan, dia melemparkan handphonenya ke atas ranjang. Benda mungil itu menyala, sebentar. Pesan terkirim, terbaca sekilas dari layarnya.
Kamu lihat, seperti hujan yang membasahi bumi, seperti itu kamu selalu berhasil menyirami hatiku.
***
*cerpen ini diikutsertakan dalam proyek @nulisbuku dengan tema #hujan
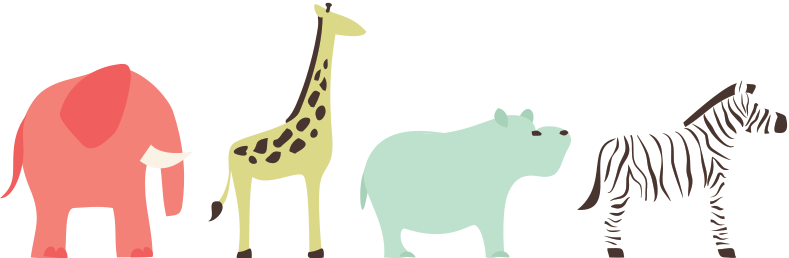

woooooww….
hasil galaunya mantab mba!!
kereeenn
LikeLike
galau adalah nama tengahku, halah hahahaha. suwun zah
LikeLike
gak sukak tulisan ini!!!!
“rasakan butiran air yang menerpamu, sebanyak itulah rasa syukurku saat tahu kau baik-baik saja disana.”
huaaaaaaa…. #bastardilove
LikeLike
hahaaha, aku gak melok-melok lho ya. selamat menggragoti aspal hahahahaha
LikeLike
Golek aspal nggo mbalang wedhus 😆
LikeLike
wooooo, duso kon, wedhus manis dianiaya
LikeLike
woi tanggung jawab, senin siangku dadi galau ki, saiki ra kerjo malah ngubek2 official website band’e deknen hahahaha, asyeeeeeeeeeeemmmm!!!
LikeLike
wah, penulis *ngaku-ngaku, padahal asline artis* tidak bertanggungjawab atas segala efek yang disebabkan oleh tulisannya, kecuali ada yang hamil hahahaha
LikeLike
melu-melu Rolland Barthes dengan the dead of the author-nya yo hahaha
LikeLike
aku ngertine Rolland Bakery, eh Holland sih hahaha
LikeLike
syahdu.. 🙂
LikeLike
bang haji 🙂
LikeLike
wes gek do kenalan..:D
LikeLike
hujan, ritmis tetesnya tak saja menyisakan keindahan…
tapi juga membuatku sadar, betapa aku membutuhkan kehangatan…
membuatku ingat jelas jalan pulang, sayang
LikeLike
ciyeeeeeeeeeeeeeee
LikeLike
hujan rindu #eh
LikeLike
hujan sehujan hujannya 🙂
LikeLike